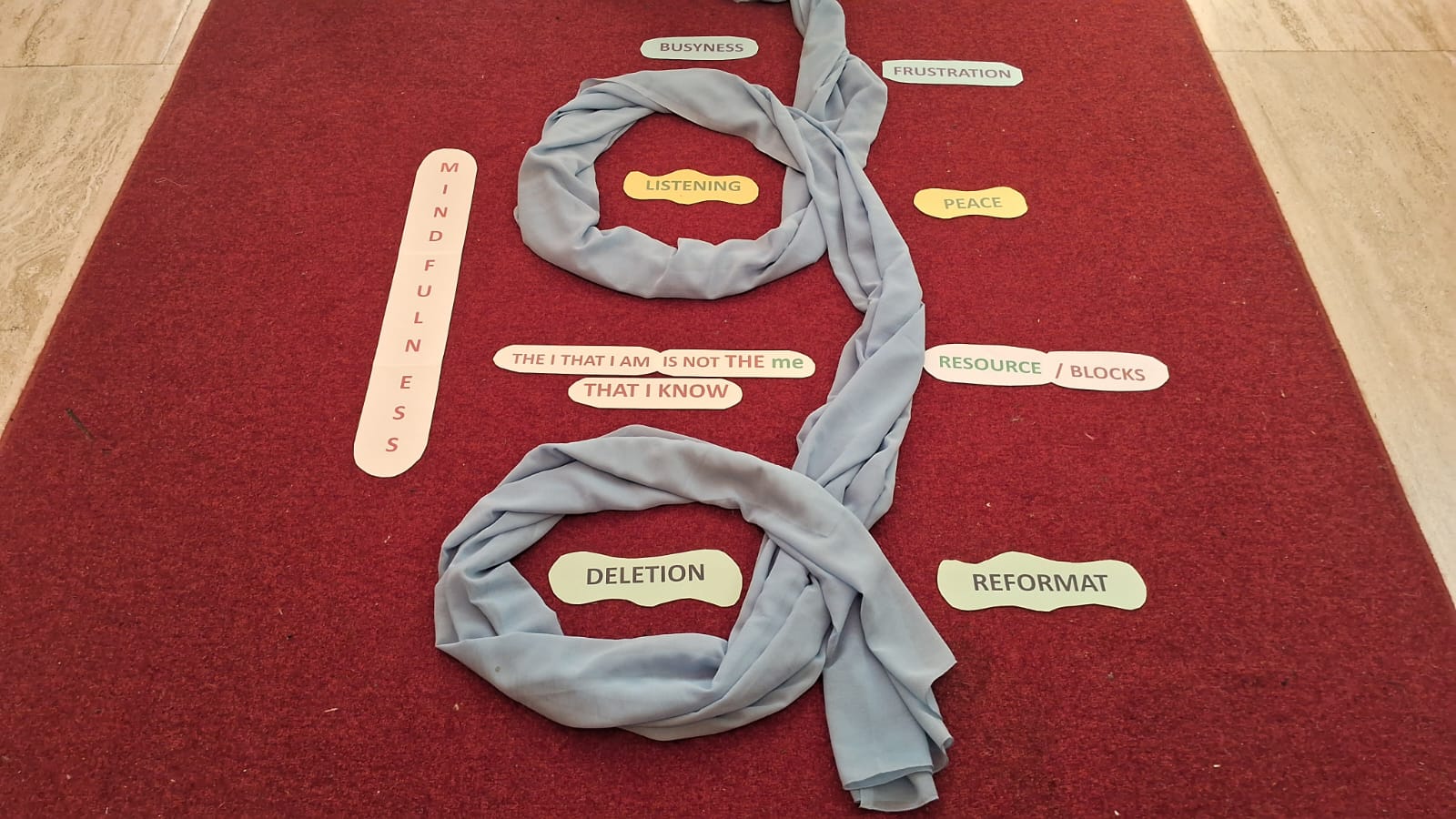Sebuah Catatan Pinggir dari Seminar OSIS SMA Seminari Todabelu
OSIS SMA Seminari St. Yohanes Berkhmans Todabelu melaksanakan seminar bertema “Peluang dan Tantangan Generasi Muda di antara Budaya Lokal dan Budaya Modern” pada Sabtu, 10 Februari 2024. Seminar ini berlangsung di Aula SMA Seminari Todabelu dan melibatkan semua siswa SMA Seminari Todabelu. Seminar tersebut menghadirkan Egwin Gawe (siswa kelas XII SMA Seminari Todabelu) sebagai Pemateri, Mitchel Pantaleon (siswi kelas XI SMAK Regina Pacis Bajawa) sebagai Penanggap I, dan Olan Nanga (siswa kelas XI SMA Seminari Todabelu) sebagai Penanggap II.
Tulisan ini mengemukakan beberapa “catatan pinggir” penulis (yang bertindak sebagai moderator) terhadap penyelenggaraan seminar dan buah-buah ide yang didiskursuskan dalam seminar. Catatan pinggir ini dibagi dalam dua bagian. Pertama, menegaskan latar belakang substantif dilaksanakannya seminar. Kedua, buah-buah pandangan dari diskursus dalam seminar.
Seminar OSIS: Membangun Kultur Akademik
Tatkala melibatkan diri dalam pembentukan kepanitiaan seminar, penulis bersama Sie Akademik OSIS menyorot soal kultur akademik yang mulai menurun dalam kehidupan para siswa di SMA Seminari Todabelu. Karena itu, salah satu upaya yang bisa diejawantahkan guna menjawab persoalan ini ialah dengan memperbanyak kegiatan ilmiah. Salah satunya ialah dengan melaksanakan kegiatan seminar.

Hemat penulis, pilihan ini sangat tepat. Seminar merupakan sebuah kegiatan ilmiah yang membahas suatu tema di bawah pimpinan pembicara atau pemakalah. Pembicara atau pemakalah ini merupakan orang yang “ahli” untuk sebuah tema yang didiskusikan.
Dalam seminar, aspek diskursus menjadi penekanan utama. Lewat sistem diskusi yang ditetapkan oleh seorang moderator, setiap orang yang terlibat dalam seminar dapat menyuguhkan pandangan-pandangannya. Pandangan-pandangan ini kemudian dikritisi secara bersama. Akhir dari seminar ialah perluasan pandangan dari tema yang telah didiskusikan – “Sebelum mengikuti seminar, orang (mungkin) memiliki bangunan konsep tersendiri terkait tema yang dibahas dalam seminar. Namun, usai seminar orang akan mendapatkan perluasan konsep, akibat pertukaran ide yang berlangsung selama seminar.”
Dengan demikian, jikalau para siswa dari waktu ke waktu mengikuti seminar, maka tentu akan mencapai tujuan-tujuan ideal dari sebuah seminar itu sendiri. Pertama, tentu dapat membentuk karakter kritis terhadap sebuah persoalan. Kedua, mampu membangun dan menata sebuah pandangan; untuk kemudian dapat disajikan atau dipertukarkan di ruang publik.
Seminar menjadi sarana bagi para siswa untuk terus hidup dari sebuah kebiasaan ilmiah. Filsuf Aristoteles pernah mengatakan: “we are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit – Kita adalah apa yang berulang kali kita lakukan. Keunggulan bukanlah sebuah tindakan, melainkan sebuah kebiasaan.”
Kamu Nanya Orang Jepang hingga Orang Jepang Bertanya Balik
Dalam Seminar tersebut, Egwin menyajikan esainya bertajuk “Kamu Nanya Orang Jepang”. Esai ini pernah menyabet juara I dalam lomba menulis esai tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Sie Akademik BEM IFTK Ledalero. Dalam esainya, Egwin mengedepankan tesis bahwa di tengah upaya modernisasi, bangsa Indonesia bisa belajar dari bangsa Jepang yang meski berkembang pesat dalam modernitasnya tetap mampu mempertahankan kehidupan budayanya.
Egwin mendasari pandangannnya dengan menilik westernisasi dan modernisasi yang sering kali dipahami secara keliru (serupa) oleh kebanyakan masyarakat Indonesia. Misalkan Egwin menampilkan sebuah ungkapan yang sebagaimana dicatat oleh Maryati dan Suryawati (2016: 38): “Anda belum modern (kolot) kalau tidak meniru budaya Barat”.
Menurut Egwin sebagaimana menukil pandangan Koentjaraningrat, modernisasi merupakan usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan keadaan dunia sekarang (Maryawati dan Suryawati, 2016: 39). Sementara westernisasi merupakan cara hidup yang meniru cara hidup Barat secara berlebihan dalam segala aspek kehidupan tanpa adanya sikap selektif – pemujaan terhadap Barat (Alfadhil, Anugrah, dan Hasbar, t.t: 101).
Selanjutnya Egwin mengangkat penggunaan ungkapan “kamu nanya” yang sempat viral di kalangan muda-mudi dan anak-anak hampir di seluruh wilayah Indonesia selama satu tahun terakhir. Bagi Egwin, tren “kamu nanya” merupakan salah satu indikasi negatif dari perkembangan modernitas di Indonesia.
Ungkapan “kamu nanya” menjadi salah satu bentuk perkembangan modernitas di Indonesia yang dalam pandangan Egwin, mengabaikan sisi etika-sopan santun dalam budaya masyarakat Indonesia.
“Ungkapan tersebut mungkin dapat dianggap sebagai bentuk candaan. Masalahnya jika ungkapan tersebut digunakan di luar konteks atau terhadap orang yang lebih tua, kesannya tidak sopan – bahkan sangat tidak sopan,” catat Egwin dalam esainya.
Egwin membuktikan pandangannnya itu dengan mengangkat kasus seorang anak yang melontarkan ungkapan “kamu nanya” untuk membalas nasihat orang tuanya sebagaimana dicatat oleh Kompas.com (22/12/2023). Terhadap kasus ini netizen Indonesia sempat geram terhadap si anak yang dinilai tidak tahu sopan santun. Namun, dalam penilaian lebih jauh, Psikolog, Rommy menyebut tindakan sang anak tersebut mengindikasikan adanya kekeliruan dalam pola pendidikan orang tuanya.

Menanggapi kasus ini Egwin menegaskan bahwa jikalau bangsa Indonesia mau berkembang dalam modernisasi yang tetap mempertahankan-melestarikan budayanya, maka bangsa Indonesia bisa bertanya (belajar) pada Jepang. Menukil Encyclopedia International (1963: 544) dan Takashi Inoguchi (seperti dikutip Sugimoto, 2006: 350), Egwin menandaskan bahwa dalam upaya modernisasinya, Jepang memiliki hasrat untuk menciptakan gagasannya sendiri dengan tidak meniru atau mengadopsi model Barat sepenuhnya, tetapi mengadaptasinya.
“Jepang mampu menghadapi globalisasi dengan berpegang pada kebudayaannya, sehingga kebudayaan itu tidak tergerus oleh globalisasi dan westernisasi,” tandas Egwin dalam esainya.
Indonesia bisa belajar dari Jepang yang melestarikan budaya di tengah modernisasi dengan terus mengajarkan (mewariskan) budaya dan nilai-nilai budaya dalam kolaborasi lewat pendidikan formal (sekolah) dan non-formal (keluarga dan masyarakat). Secara khusus dalam upaya pelestarian budaya – nilai-nilai moral di tengah upaya modernisasi, Indonesia bisa belajar dari Jepang yang meletakkan pendidikan moral dalam porsi yang lebih, baik di lingkungan pendidikan sekolah (SD hingga SMA), keluarga, hingga masyarakat.
“Dengan demikian generasi muda dapat dibentuk menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh berpegang pada nilai-nilai budaya, memiliki kearifan lokal, dan mampu mengambil sikap terhadap pengaruh budaya yang negatif,” pungkas Egwin dalam esainya.
Selanjutnya dari tanggapan yang disajikan oleh Mitchel Pantaleon dan Olan Nanga, serta dari tiga sesi diskusi yang berlangsung dalam seminar, terdapat beberapa pandangan yang bisa dirangkum dalam catatan sekaligus pandangan penulis sebagai moderator. Tesis Egwin yang menegaskan bahwa bangsa Indonesia dapat belajar dari model modernisasi Jepang, mesti ditilik lebih jauh.
Pertama, hal ini mengingat tidak semua wilayah di Indonesia yang mau bergerak dalam modernisasi. Masih terdapat pula beberapa wilayah (suku) di Indonesia yang terkesan eksklusif terhadap pengaruh asing. Kedua, konteks kedua negara yang cukup berbeda dalam beberapa aspek kehidupan (kapabilitas), tentu melahirkan upaya yang berbeda pula untuk melestarikan budaya di tengah modernisasi. Dengan demikian, karena perbedaan konteks, maka seperti yang ditegaskan Olan di akhir esainya: “Indonesia ‘setengah mati’ melewati rintangan modernisasi dan bahkan westernisasi kendati berguru dari Jepang. Judul Esai Egwin ‘Kamu Nanya Orang Jepang’ bisa saja dibalikkan menjadi ‘Orang Jepang Balas Bertanya’.” (Fr. Bayu Tonggo)