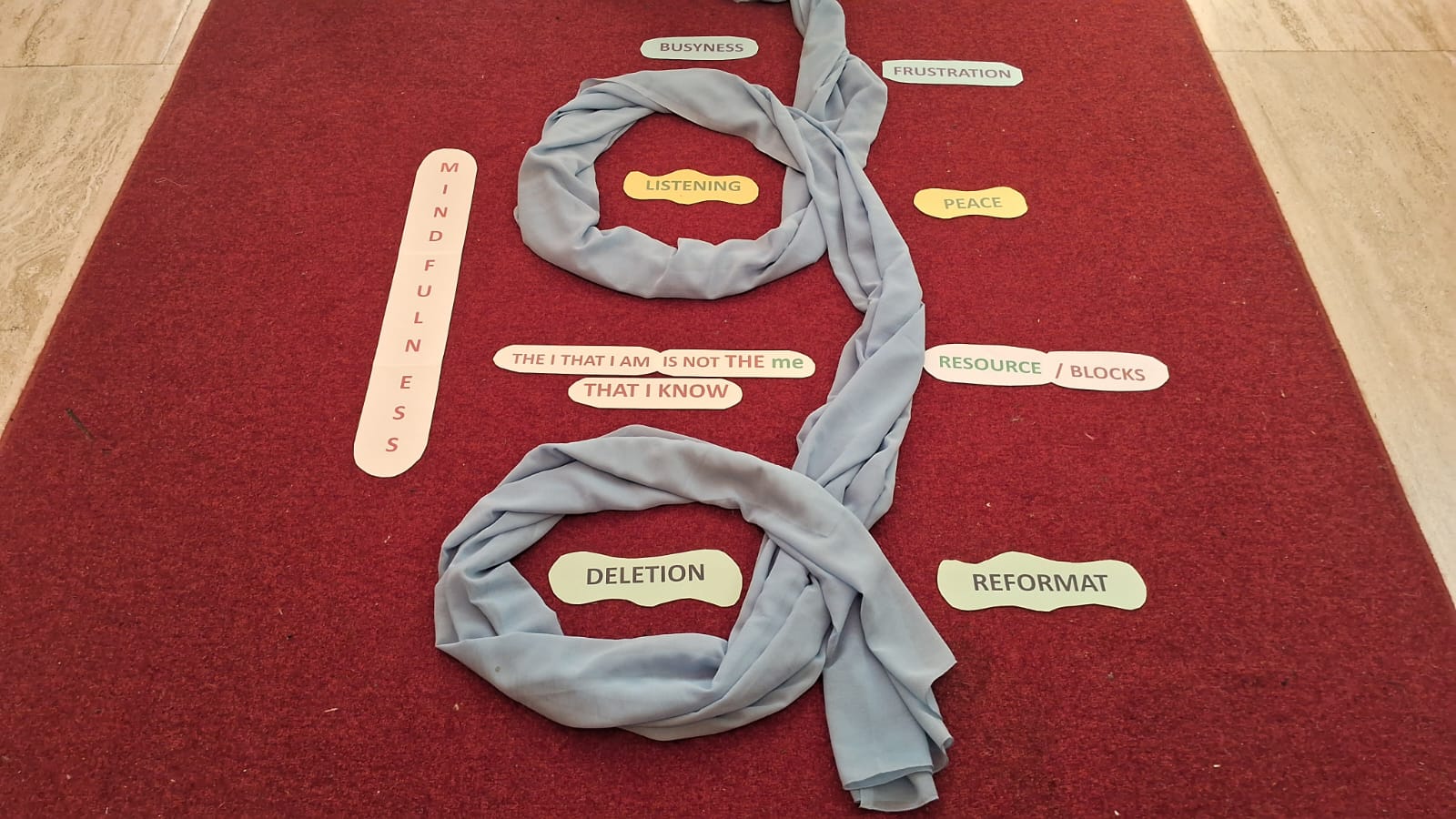Tulisan Eman Pitamini
Setelah menamatkan sekolah dasar Manasari, Mimika, Papua, saya belum berpikir ke mana saya akan melanjutkan sekolah menengah pertama. Suatu ketika, bapa memanggil saya saat pulang dari pantai. “Eman, bapa mau bicara dengan ko sebentar malam,” kata bapa. “Ko tra bole ke mana-mana malam ini,” lanjut bapak. “Io bapa” jawabku singkat. Saya berpikir sejenak. “Apa yang mau bapak bicarakan dengan saya?” gumamku dalam hati.
Karena hari masih sore, saya pergi bermain bola dengan teman-teman. Kami menuju lapangan bola untuk bermain bersama. Saya sangat menikmati pengalaman sore itu.
“Main makan daginglah”, teriak teman saya. Sepenggal kalimat itu biasa kami ucapkan saat bermain bola. Maksudnya, kami menendang bola ke tubuh teman. “Jai” (Papua Fanamo: Mari!) balas teman-temanku yang lain. Kami bermain dengan gembira. Permainan ini membuat saya melupakan pertanyaan bapak di kepala saya.
Malam tiba. Saya tidak keluar rumah, karena saya harus menuruti permintaan bapak saya. Saya pun menikmati susu di depan teras rumah. “Eman, ko mari dolo, makan sama-sama deng bapa,” panggil bapa saya. “Iyo bapa” jawab saya singkat.

Bapa memimpin doa makan. Dia mengambil nasi dan lauk serta sayur yang tersedia. Begitu pula mama, kakak, lalu saya yang di urutan terakhir.
“Anak”, bapa membuka percakapan sambil mengarahkan pandangannya kepadaku. “Ko mau lanjut SMP di mana?” Sejenak saya terdiam. Tidak tahu harus menjawab bagaimana. “Saya mau lanjut di Manado,” kata saya. Nama kota itu keluar begitu saja, kebetulan terlintas di kepala. “Ibu guru ada tawar ko untuk sekolah di Seminari di Flores”, kata bapa dengan hati-hati. Saya terdiam.
Di sekolah kami ada dua ibu guru dari Flores, Ibu Lian dan Ibu Vivin. Jadi nama Flores sudah akrab di telinga saya. Namun Seminari tidak saya ketahui sama sekali. Saya belum tahu jika Seminari adalah sekolah untuk menjadi calon imam. Bapa mengajak saya untuk berdialog terlebih dahulu dengan kedua ibu guru itu.
Saya disarankan tinggal di rumah Sekretaris Keuskupan Timika. “Supaya ko belajar berdoa, juga cuci pakaian sendiri, dan merapikan tempat tidur,” begitu kata Ibu Lian. Di sana, saya mendapatkan tambahan pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika.

Suatu waktu, saya diberitahu untuk mengerjakan soal-soal Bahasa Indonesia serta Matematika. Soal Bahasa Indonesia bermacam-macam, antara lain, membuat sebuah cerita. Saya mengerjakannya sebisaku. Malam harinya, saya menyerahkan semua hasil jawaban saya kepada Bapak Beni, Sekretaris Keuskupan. Dia bapa asuh saya. Dia berasal dari Mauponggo, Nagekeo, NTT. Dari Pak Beni, saya kemudian mendapat berita, diterima di Seminari Mataloko.
Kami berangkat dari Timika menuju Makasar menggunakan pesawat. Pak Beni mengantar saya, bersama istri dan anak perempuannya. Dalam perjalanan, saya terdiam. Terpaku sendiri. Banyak pertanyaan yang muncul dan ingin saya sampaikan kepada Bapa Beni. Namun saya tidak berani mengungkapkannya. Flores itu seperti apa? Mataloko itu bagaimana? Siapa yang mengasuh saya kalau Bapak Beni dan keluarganya kembali ke Timika? Bagaimana saya bisa berkontak dengan bapa dan mama, kakak, dan adik. Saya sedih, dan galau, tapi saya simpan rapat-rapat dalam hati.
Kami tiba di Makasar pada siang hari. Bapa Beni memesan hotel Vave yang ada di tepi pantai Makasar. Bapa Beni memesan dua kamar. Setelah menikmati makan malam bersama, kami berjalan-jalan di pantai Losari. Di situ ada festival yang diselenggarakan oleh pemerintah setempat. Sejenak saya melupakan kegalauan saya.
Saat perjalanan pulang pertanyaan-pertanyaan itu menghantui saya lagi. Saya tidak menyadari bahwa di depan saya ada saluran air. Saya terperosok ke dalam saluran tersebut. Orang-orang di sekitar saya sontak memandangi saya. Lalu saya bangkit berdiri dan pergi dengan rasa malu.
Di hotel saya bergegas menuju kamar saya lalu menelepon bapa saya. Saya menceritakan pengalaman saya. Bapa sangat senang mendengarkan suara saya. Dia membesarkan hati saya. “Ko tra pa pa. Pasti ada yang membantu,” katanya. Dia tertawa. Namun saya tahu bahwa di balik tawa tersebut ada rasa sedih yang tersembunyi. Saya berjanji kepada bapa bahwa saya akan belajar dengan baik di Seminari nanti.
Kisah awal saya masuk Seminari sederhana. Namun ini telah mengantar saya sampai di kelas XI di Seminari ini. Saya masih bertahan di sini. Dan kata-kata bapa benar. “Ko tra pa pa. Pasti ada yang membantu”. Bukan hanya itu. Saya merasa berkembang di sini, di Mataloko, di Flores.
Saya bertekad menyelesaikan pendidikan saya. Tuhan membimbing saya melalui hal-hal yang sederhana, sampai bertahun-tahun di Seminari Mataloko. Dia pasti akan terus membimbing saya ke jalan yang Dia tunjukkan (Eman Pitamini, siswa kelas XI Seminari Mataloko).