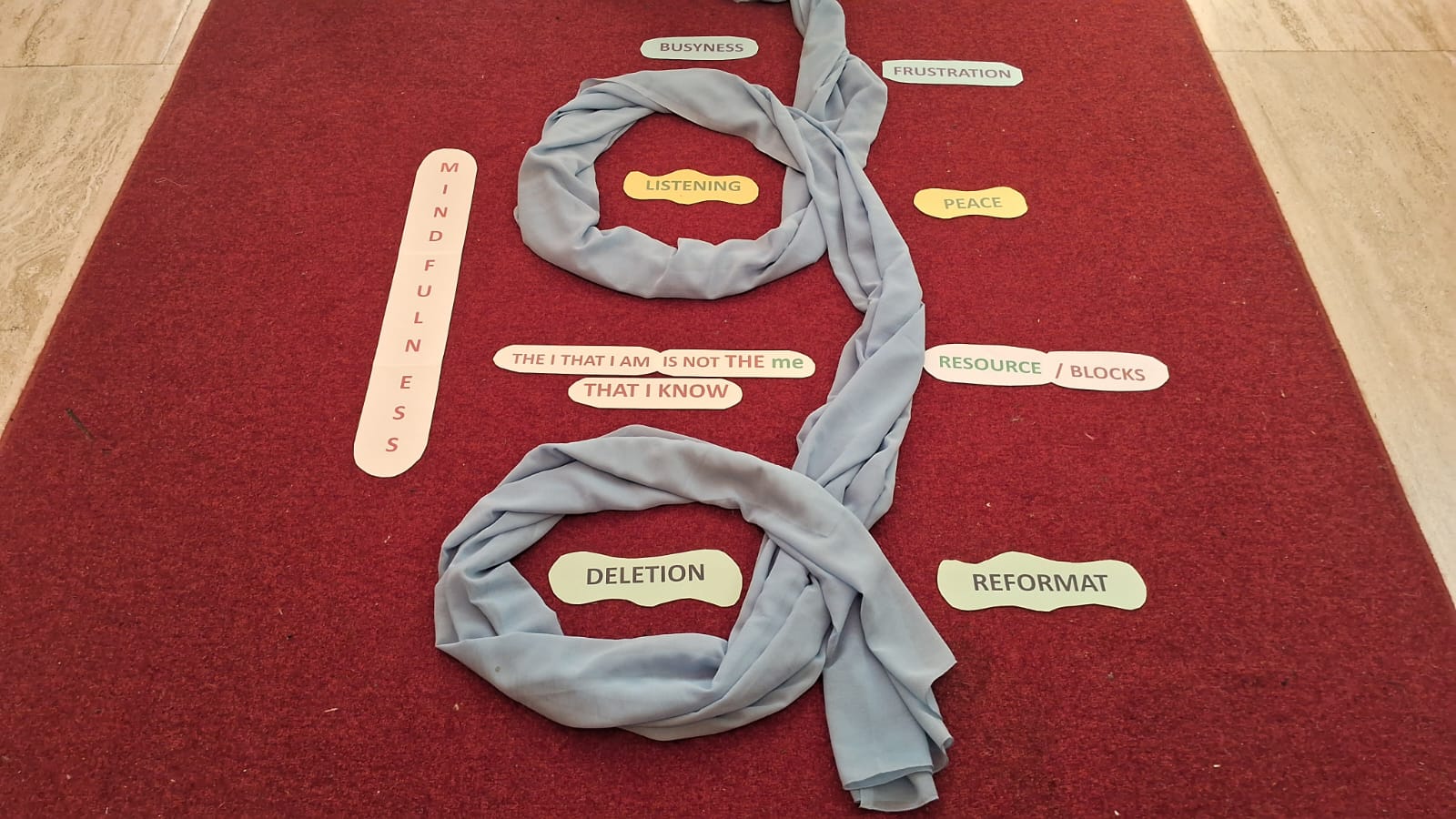Sebuah Refleksi
Siswa Seminari sekarang sudah banyak berubah. Saya ingat kata-kata Ibu Merlin, Calon Guru Penggerak (CGP) dari sekolah kami tatkala mempresentasikan materinya di hadapan kami dalam kegiatan pendampingan individu, “Guru harus menyesuaikan pelajaran dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik.” Saya dan Fr. Bayu sebagai mantan muridnya mengangguk-angguk. Rasanya kami kembali menjadi murid dan Ibu Merlin sedang mengajar Kimia seperti beberapa tahun lalu. Saat itu, kerumitan perhitungan rumus-rumus kimia menjelma lirik-lirik puisi karena ibu guru kami cantik dan keibuan. Sekarang kami menjadi rekan guru.

Saya yakin adik-adik seminaris memang berkembang menurut dua kodrat itu. Banyak hal berubah: gaya hidup, pembawaan diri, penampilan, minat, gaya belajar, gaya bicara, sikap, mental, pemikiran. Sebagai “guru”, kami memang harus tangkas dan cerdas beradaptasi. Ah, gelar “guru” tampaknya terlalu mahal untuk saya.
Untunglah, kami frater-frater masih sama-sama Gen Z dengan para seminaris. Cukup mudah jadinya untuk melebur dan membantu tumbuh kembang mereka. Namun, hal ini juga menjadi pukulan tersendiri bagi kami tatkala banyak guru senior menampakkan kemampuan adaptasi yang luar biasa.
Alhasil, kami diam-diam memacu diri sambil menghibur diri dengan pikiran “Kami kan tidak mengenyam pendidikan guru.” Proses belajarnya menjadi ganda, malah tripel. Kami mempelajari bahan ajar sekaligus cara ajar sambil mengajar. Untunglah relasi kakak-adik juga persahabatan dengan seminaris melahirkan iklim kelas yang humanis.
Tentu saja dalam proses itu, kami banyak belajar. Bahkan kadang-kadang kami kewalahan. “Kae, macam tidak ada jeda, e. Kita harus buat ini, buat itu meski sebenarnya belum siap,” komentar Fr. Bayu, rekan toper sekaligus adik tingkat setahun. Fr. Yuda, pemuda Batak yang selalu tampil necis, tersenyum mengiyakan. Saya tidak berkomentar, terutama karena saya yakin kedua sosok yang selalu tersenyum dan penuh antusiasme ini akan menemukan jawabannya.
Kalau ada kebajikan yang paling saya serapi setiap hari, itu adalah “Belajarlah, baik atau tidak baik waktunya!” Ini adalah adaptasi saya dari moto tahbisan Alm. Bapak Uskup Vinsen Sensi. Kemarin, beliau berpulang ke Rumah Bapa. Sedih rasanya. Suasana seminari kemarin malam terasa mencekam. Seminaris akhirnya bisa menghayati silentium magnum (hening besar). Requiescat in pace…
Salah satu hal yang membuat saya iri dari pendidikan seminaris kini ialah metode belajar bahasa Inggris yang modern. Mereka terbiasa mengakses situs dan aplikasi belajar bahasa Inggris berbasis digital dan membangun jejaring belajar secara internasional. Sungguh suatu kemewahan! Hal lainnya ialah pengembangan kegiatan ekstrakurikuler serta kokurikuler yang menarik dan eksploratif. Hal ini membantu para seminaris untuk mengekspresikan diri dan membangun rasa percaya diri yang sehat.

Setiap peluang selalu menghadirkan tantangan baru. Generasi kami beberapa tahun lalu masih mengalami tuntutan pembelajaran yang tinggi—“high-demanding”, begitulah Rm. Nani menyebutnya—dalam ruang dan fasilitas belajar yang belum serba instan, meskipun sungguh tidak bisa dikatakan seadanya. Akibatnya, kami harus memacu diri lebih keras, mengoptimalkan segala daya upaya, dan membangun kemandirian belajar. Namun, tantangan generasi sekarang ialah memanfaatkan segala kemudahan belajar dan kesempatan pengembangan potensi diri tanpa jatuh pada mentalitas serba instan, ikut rame, dan minimalis. Yang terakhir ini memang sering salah diartikan sebagai sikap apa adanya.
Ah, sudahlah. Bicara generation gap memang tidak menyenangkan. Siapa yang bisa menjamin pandangan ini objektif? Lain halnya kalau yang berbicara tentang hal ini ialah para pembina dan guru senior di Seminari ini.
Manusia, kehidupan, dan dunia itu dinamis. “Panta rhei”, semuanya mengalir, demikian kata Heraclitus. Sungguhkah semua hal berubah? Apakah semua perubahan harus dimaklumi?
Mungkin kita bisa menengok sungai. Meski air mengalir, sungai toh masih dikenali sebagai sungai juga. Meski beradaptasi dengan perkembangan zaman, identitas keseminarisan harus tetap dijaga. Tidak baik kalau hal yang prinsipiel dan esensial dikorbankan semata-mata demi ikut tren. Untuk seminaris, marwah identitas itu ialah kelima pilar pendidikan yang dikenal dengan 5S: sanctitas (kekudusan/kerohanian), sanitas (kesehatan), scientia (pengetahuan), sapientia (kebijaksanaan), dan socialitas (kemasyarakatan/persaudaraan). Romo Aleks pernah berbicara keras tentang hal ini di ruang guru. Seisi ruangan hening mendengarkan.

Dalam suatu pembicaraan lepas di unit C, Rm Tinyo, Kepsek SMA pernah berceletuk, “Ini mendidik manusia, ni… tidak gampang.” Saya yang mendengar itu berhenti tertawa dan tertegun. Bahasa lepas itu membekas dalam hati saya dan berdengung kembali di momen-momen tertentu dalam kebersamaan dengan seminaris.
“Zaman sudah berbeda, Ef-er,” demikian keluh seminaris kalau dinasihati. Kepada para frater memang siswa sering terbuka, bicara apa adanya. Mereka menjadi ceplas-ceplos dengan pemikiran, perasaan, protes, dan keberatannya. Kami mafhum. Dengan semua kenakalan, cengar-cengir, tindak-tanduk, kepolosan, ambisi, pertanyaan, dan alasan, mereka bak adik-adik yang butuh perhatian. Akan tetapi, perhatian itu tidak mesti berwujud senyum dan pengiyaan demi pengiyaan.
Suatu waktu, saya meminta siswa berdiskusi. Karena keseruan dan kelucuan diskusi itu, seminaris bereaksi dengan tertawa terbahak-bahak, memukul meja, dan berteriak. Keesokan harinya saya memberitahu mereka bahwa antusiasme tidak sama dengan barbarisme. Dalam pendidikan, ada nilai yang mesti dijunjung. Ruang kelas jangan sampai membenihkan relativisme yang tampaknya membebaskan, tetapi sesungguhnya ilusif.
Sesungguhnya bukan hanya siswa yang belajar. Sebagai frater TOP sekaligus pembina yang tak sempurna, saya dan teman-teman toper lain pun belajar. Belajar adalah keniscayaan. Seminaris dan lingkungan seminari turut mendewasakan frater TOP-nya. Sebab seperti adik-adik seminaris yang bergumul dengan panggilannya, kami pun demikian.
Lagi-lagi saya harus mengulang afirmasi biblis dari rekan toper saya tahun lalu, Fr. Blas, “Kami adalah hamba-hamba yang tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.”
Frt. Pance Dhae
Sedang menjalani TOP di Seminari Mataloko