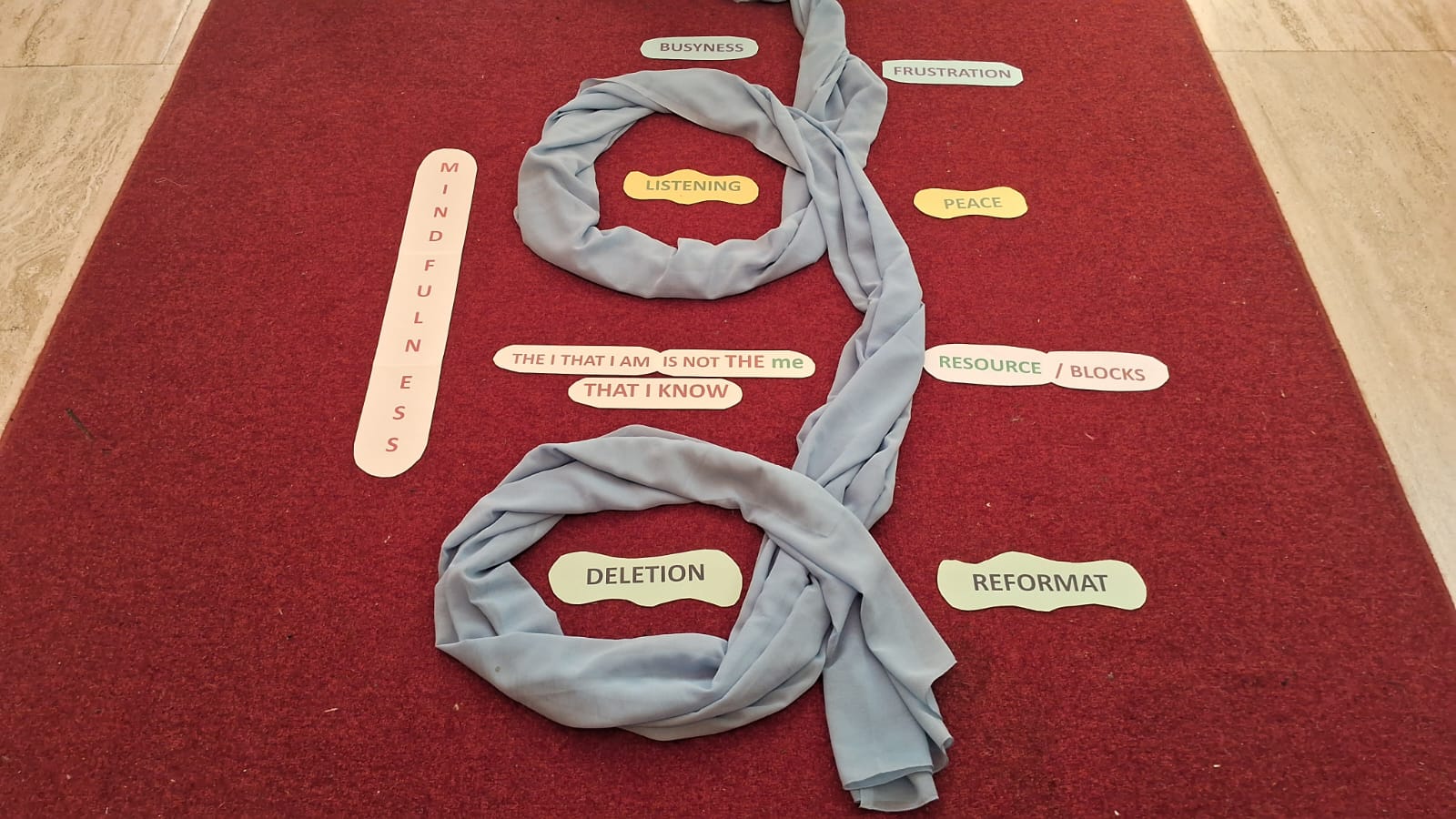Wenggo ulu eko adalah ritus adat Lio, Flores, yang dimulai sejak tahun 1800-an karena lowa moa (kelaparan) melanda kawasan tersebut. Mosalaki lalu membuat ritus ini sebagai respons. Kegiatan ini diyakini sakral sehingga larangannya mengikat.
Ritus adat bukanlah hal baru dalam kehidupan masyarakat Lio. Dalam menjalani kehidupan, masyarakat Lio cenderung berpegang teguh pada kuasa yang disebut Nggae. Mereka juga mengakui peran leluhur dalam sendi kehidupannya. Hal-hal semacam ini tercurah dalam berbagai aktivitas kehidupan mereka.
Contohnya, kegiatan wenggo ulu eko yang dibuat oleh masyarakat Desa Tou, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende. Ritus ini mereka yakini sebagai ritual guna mempersiapkan tanah sebagai media persemaian benih, ketika musim tanam tiba.
Kegiatan ini dimulai kurang lebih pada awal tahun 1800-an. Kegiatan ini biasanya dibuat bulan Oktober. Pemilihan bulan dimaksudkan agar dekat musim tanam.
Latar belakang wenggo ulu eko adalah terjadinya lowa moa (kelaparan) di Detukou dan sekitarnya karena apa pun yang mereka usa-hakan tidak membuahkan hasil. Masyarakat meyakini bahwa hal itu terjadi karena ada pengaruh dari leluhur.
Menanggapi hal ini mosalaki (tokoh adat) setempat melakukan ritual wenggo ulu eko sebagai respons atas masalah tersebut. Hal ini membawa dampak positif bagi masyarakat pada masa itu. Karena itu, diputuskan, wenggo ulu eko mesti dijadikan kegiatan rutin oleh masyarakat setempat.
Awalnya, kegiatan ini akan dimulai oleh masyarakat adat setempat tanpa kecuali. Hal ini dimaksudkan agar tanah dan kebun yang masyarakat miliki mendapatkan kesuburan.
Masyarakat yang hadir dalam ritus, biasanya mewakili keluarganya. Biasanya terdiri atas 6 golongan, yaitu Ata Kune, Ata Tu, Ata Loke, Ata Henda, Bhajo Wawo, Ana Mbete dan Fai Walu Ana Halo (masyarakat biasa).
Masyarakat yang berkumpul mengabdi pada satu mosalaki yang disebut Tana Jogo Watu Laki Mari. Mosalaki yang memimpin jalannya kegiatan berasal dari golongan Ana Mbete. Dapat dikatakan, Ana Mbete adalah kepala semua golongan.
Dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemimpin, seorang mosalaki dibantu Ana Hage (kaki tangan mosalaki) yang terdiri dari Ata Kune, Ata Tu, Ata Loke, Ata Henda, dan Bhajo Wawo.
Masyarakat yang datang biasanya membawa seekor ayam, sebotol moke (arak) dan beras. Bawaan ini menjadi persembahan yang akan diletakkan pada musu mase (batu persembahan) dan dimasak sebagai hidangan makan bersama.
Acara ini akan dimulai dengan pemanggilan masyarakat berdasarkan kampung. Saat dipanggil, biasanya beras yang dibawa akan dikula (diukur). Kemudian dimasak oleh Fai Gamo Lima (istri dan keluarga besar mosalaki).
Setelah dipanggil, semua golongan masyarakat berkumpul di depan rumah adat induk. Setelah berkumpul, mosalaki akan melakukan ritual riwu rera (memberi sesajian kepada leluhur). Hidangan sebagai sajian mesti sesuai dengan apa yang diwariskan leluhur, yakni are manu nagi dan are kola kedhe.
Sajian kola kedhe yang dibuat mesti mengandung bahan udang. Selama proses riwu rera, semua orang tidak diperkenankan membuat kegaduhan. Hal ini menunjukkan, kegiatan ini sakral. Mereka juga meyakini bahwa kegaduhan dapat menyebabkan permohonan tidak dikabulkan.
Setelah riwu rera, kegiatan ritual dilanjutkan dengan makan bersama. Saat makan, masyarakat tidak memakai peralatan modern, tapi menggunakan peralatan tradisional yang disebut pene ha’i. Hidangan makan bersama yang disediakan dimasak oleh Fai Gamo Lima.
Proses memasak hidangan dimulai dengan ngaki loka (membersihkan lokasi masak). Hal ini biasanya dibuat golongan Bhajo Wawo dan Ata Henda.
Setelah ngaki loka, kegiatan dilanjutkan dengan tabha are tana nasu nake watu (memasak), baik sesajian maupun hidangan ka bou pesa mondo (makan bersama).
Setelah kegiatan ritual berlangsung, masyarakat, baik yang hadir maupun yang berada di rumah, diminta untuk menaati larangan, seperti, tidak menyisir rambut, tidak menyapu rumah, tidak gaduh, dan tidak membawa tumbuhan hijau masuk kampung selama satu hari.
Larangan yang dibuat akan berlanjut hingga hari yang ditentukan. Larangan paling akhir biasanya berlaku pada hari sebelum mosalaki melakukan paki (penanaman benih), masyarakat dilarang melakukannya lebih dahulu.
Jika larangan tidak ditaati, denda akan dikenakan. Sanksi yang disebut seliwu se’eko terdiri atas seekor babi dan sejumlah uang. Dulu, sebelum menggunakan uang, denda dibayar dengan emas.
Namun, denda ini hanya dikenakan kepada mereka yang kedapatan menyimpang. Bila melakukan penyimpangan, tapi tidak kedapatan, rusaknya struktur tanah dan gagal panen diyakini sebagai sanksi yang diberikan leluhur. Setelah selesai, biasanya akan dilanjutkan dengan gawi bersama jika memungkinkan.
Saat ini, wisatawan asing boleh menghadiri kegiatan, tapi harus atas izin mosalaki. Mereka ini disebut sebagai kura fangga no’o lowo lowo ro’a loka no’o keli keli (pendatang). Jika wisatawan melakukan pelanggaran pertama kali, mereka akan ditegur.
Bayu Putra
Siswa kelas XI SMA Seminari Todabelu, Mataloko