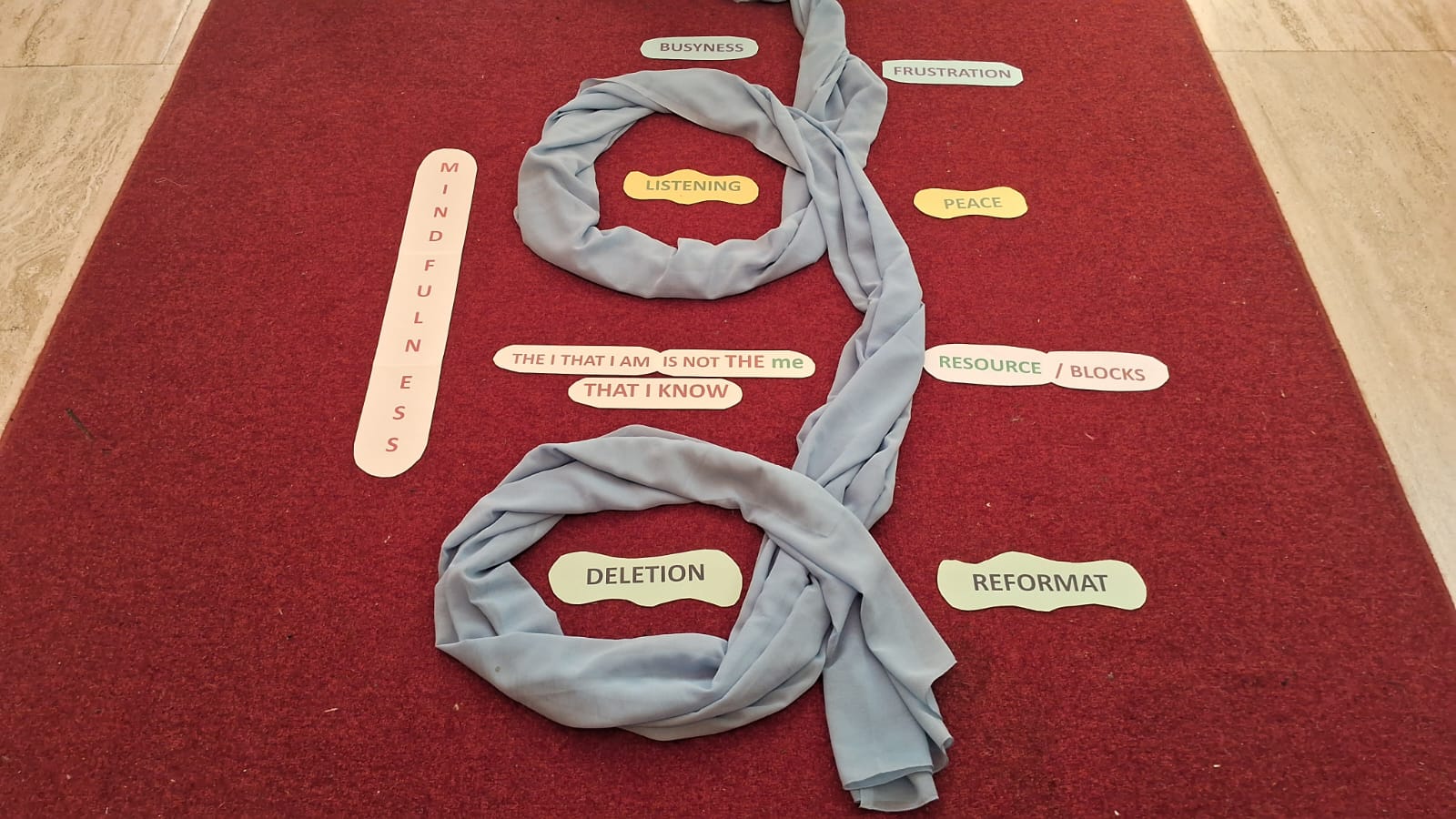Menjelang pemilu legislatif dan pilpres 2019, sebagai tahun politik, dan (menurut saya) tahun fitnah dan kebohongan, sebaiknya kita (termasuk saya) belajar sedikit mengenai psikologi massa. Sudah banyak, bahkan tak terhitung teman-teman kita di media sosial yang mengingatkan teman yang lain untuk berpikir sebelum bicara, tabayyun sebelum menulis suatu hal, klarifikasi sebelum share status. Namun status-status ngawur-ngawuran, komen fitnah maupun yang mendekati fitnah, tudingan-tudingan kanan-kiri, ad hominem, share berita bohong, atau berita yang ternyata bohong, maksudnya tadinya haqul yakin beritanya benar, eh ternyata berita bohong, atau pernyataan tidak benar, lalu terlanjur gengsi untuk mengklarifikasi. Tentu saja termasuk dari saya sendiri. Teguran dan peringatan ini biasanya tidak ngefek. Konon sumber hoax tidak banyak dan hanya dari kelompok tertentu yang ingin memecah belah bangsanya sendiri. Saya tidak akan membahas sumbernya dari mana, yang saya bahas bagaimana selama ini kita meresponnya. Kita tiba-tiba bisa benci dengan seseorang begitu mendalam hanya karena membaca status. Bahkan dengan orangnya saja tidak kenal, ketemu juga belum pernah, apalagi ngobrol. Memang media sosial bisa jadi ajang kampanye positif seperti sedekah rombongan, atau komunitas tolong-menolong seperti Info Cegatan Jogja (ICJ). Tapi tidak kalah banyak jadi ajang hujat dan caci maki. Tanpa sadar, kita menikmatinya. Lho? Iya, saat menyalurkan kebencian sambil jempol sibuk di smartphone itu otak kita juga menyemburkan dopamine. Dalam kadar yang berbeda, dopamine juga yang disemburkan otak ketika kita orgasme (bagi yang sudah pernah). Dopamine adalah neurotransmitter di dalam otak yang mengatur perasaan senang, puas, dan nikmat. Apalagi kalau status kita direspons oleh status lain baik yang mendukung maupun yang balik mencaci. Semburannya makin kencang ketika kita merasa “menang” saling hujat atau lawan berantem kita lalu diam saja. Kepuasannya semakin menjadi-jadi. Dalam novel “1984” Karya George Orwell. Masyarakat totalitarian dikumpulkan Dalam sebuah auditorium setiap minggu untuk event “two minutes hate” atau “dua menit kebencian” untuk bersama-sama menghujat dan mencaci maki “musuh” negara. Bahkan Winston Smith, si protagonis yang diam-diam seorang pemberontak yang juga bisa disebut “musuh” negara, ikut larut dalam kebencian. Katanya “A hideous ecstasy of fear and vindictiveness, a desire to kill, to torture, to smash faces in with a sledgehammer, seemed to flow through the whole group of people like an electric current, turning one even against one’s will into a grimacing, screaming lunatic.” Artinya “Kegairahan yang mengerikan akan ketakutan dan dendam, hasrat untuk membunuh, menyiksa, untuk menghantam muka orang dengan palu, semuanya seperti mengalir, menyembur dalam kerumunan atau kelompok seperti aliran listrik, mengubah tiap orang dalam kelompok menjadi wajah-wajah yang menakutkan.” Harap maklum saya lampirkan versi aslinya dalam bahasa Inggris, karena siapa tahu terjemahan saya salah. Media sosial adalah kerumunan massa. Dalam kerumunan, individu menjadi anonymous, kehilangan identitas. Individu dalam kerumunan kehilangan tanggung jawab pribadinya, secara ekstrim kehilangan rasa malunya, rasa hormatnya pada manusia lain di luar kelompoknya (out-group), bahkan moralitas bisa lenyap. Apalagi banyak akun media sosial yang tidak menunjukkan identitas sebenarnya. Ada yang pernah ikut demonstrasi? Bersama ribuan orang kita berteriak-teriak menuntut sesuatu, dengan satu-dua provokasi setiap orang bisa jadi beringas dan berani melakukan apa saja. Hanya meriam air dan gas air mata yang bisa membubarkannya. Kerumunan ini tidak hanya di jalanan, tapi juga di dunia maya, kebencian akan semakin menjadi apabila ada provokasi, apalagi yang memprovokasi satu “kelompok” dengan kita (in-group), bisa kelompok agama, kelompok suku, kelompok preferensi, bahkan hanya karena warna baju yang sama. Pada masa perang dunia kedua antara tahun 1941-1945, ada seorang guru Jerman yang dihormati oleh siswa-siswanya sebelum perang. Ketika perang pecah dan orang ini menjadi penjaga kamp konsentrasi di Dachau, olah raganya tiap pagi menembaki penghuni kamp sampai mati secara acak untuk menghilangkan bosan. Bagaimana mungkin? Bisa saja, karena semua orang sebangsanya menganggap ras yang dia tembaki (Yahudi, out-group) lebih rendah dari manusia. Dia jadi anonymous di antara bangsanya (Bangsa Arya, in-group), tanggung jawab dan moralitasnya menguap. Menurut teori identitas sosial : In-Group & Out-Group, seseorang bisa dimanipulasi dalam dinamika psikologi massa. Fenomena konformitas individu dalam kelompok macam ini juga pernah diteliti oleh Dr. Philip George Zimbardo, profesor psikologi dari Universitas Stanford pada Agustus 1971. Penelitiannya terkenal dengan nama Standford Prison Experiment. Zimbardo merekrut sukarelawan untuk ikut penelitiannya. Mereka dibayar sama per hari. Ketika dimulai, peserta dibagi secara acak. Satu kelompok menjadi penjaga, satu kelompok menjadi tahanan. Dibuatkan penjara-penjaraan di gedung kampus. Eksperimen direncanakan berjalan 2 minggu. Mereka dibebaskan improvisasi dan diberi seragam yang berbeda antara penjaga dan tahanan. Baru dua hari berjalan, kelompok penjaga sudah memukuli tahanan yang tidak patuh, sementara kelompok tahanan luar biasa takut dengan penjaga dan berusaha “kabur” dari penjara. Padahal mereka bisa saja meminta untuk berhenti.
Menjelang pemilu legislatif dan pilpres 2019, sebagai tahun politik, dan (menurut saya) tahun fitnah dan kebohongan, sebaiknya kita (termasuk saya) belajar sedikit mengenai psikologi massa. Sudah banyak, bahkan tak terhitung teman-teman kita di media sosial yang mengingatkan teman yang lain untuk berpikir sebelum bicara, tabayyun sebelum menulis suatu hal, klarifikasi sebelum share status. Namun status-status ngawur-ngawuran, komen fitnah maupun yang mendekati fitnah, tudingan-tudingan kanan-kiri, ad hominem, share berita bohong, atau berita yang ternyata bohong, maksudnya tadinya haqul yakin beritanya benar, eh ternyata berita bohong, atau pernyataan tidak benar, lalu terlanjur gengsi untuk mengklarifikasi. Tentu saja termasuk dari saya sendiri. Teguran dan peringatan ini biasanya tidak ngefek. Konon sumber hoax tidak banyak dan hanya dari kelompok tertentu yang ingin memecah belah bangsanya sendiri. Saya tidak akan membahas sumbernya dari mana, yang saya bahas bagaimana selama ini kita meresponnya. Kita tiba-tiba bisa benci dengan seseorang begitu mendalam hanya karena membaca status. Bahkan dengan orangnya saja tidak kenal, ketemu juga belum pernah, apalagi ngobrol. Memang media sosial bisa jadi ajang kampanye positif seperti sedekah rombongan, atau komunitas tolong-menolong seperti Info Cegatan Jogja (ICJ). Tapi tidak kalah banyak jadi ajang hujat dan caci maki. Tanpa sadar, kita menikmatinya. Lho? Iya, saat menyalurkan kebencian sambil jempol sibuk di smartphone itu otak kita juga menyemburkan dopamine. Dalam kadar yang berbeda, dopamine juga yang disemburkan otak ketika kita orgasme (bagi yang sudah pernah). Dopamine adalah neurotransmitter di dalam otak yang mengatur perasaan senang, puas, dan nikmat. Apalagi kalau status kita direspons oleh status lain baik yang mendukung maupun yang balik mencaci. Semburannya makin kencang ketika kita merasa “menang” saling hujat atau lawan berantem kita lalu diam saja. Kepuasannya semakin menjadi-jadi. Dalam novel “1984” Karya George Orwell. Masyarakat totalitarian dikumpulkan Dalam sebuah auditorium setiap minggu untuk event “two minutes hate” atau “dua menit kebencian” untuk bersama-sama menghujat dan mencaci maki “musuh” negara. Bahkan Winston Smith, si protagonis yang diam-diam seorang pemberontak yang juga bisa disebut “musuh” negara, ikut larut dalam kebencian. Katanya “A hideous ecstasy of fear and vindictiveness, a desire to kill, to torture, to smash faces in with a sledgehammer, seemed to flow through the whole group of people like an electric current, turning one even against one’s will into a grimacing, screaming lunatic.” Artinya “Kegairahan yang mengerikan akan ketakutan dan dendam, hasrat untuk membunuh, menyiksa, untuk menghantam muka orang dengan palu, semuanya seperti mengalir, menyembur dalam kerumunan atau kelompok seperti aliran listrik, mengubah tiap orang dalam kelompok menjadi wajah-wajah yang menakutkan.” Harap maklum saya lampirkan versi aslinya dalam bahasa Inggris, karena siapa tahu terjemahan saya salah. Media sosial adalah kerumunan massa. Dalam kerumunan, individu menjadi anonymous, kehilangan identitas. Individu dalam kerumunan kehilangan tanggung jawab pribadinya, secara ekstrim kehilangan rasa malunya, rasa hormatnya pada manusia lain di luar kelompoknya (out-group), bahkan moralitas bisa lenyap. Apalagi banyak akun media sosial yang tidak menunjukkan identitas sebenarnya. Ada yang pernah ikut demonstrasi? Bersama ribuan orang kita berteriak-teriak menuntut sesuatu, dengan satu-dua provokasi setiap orang bisa jadi beringas dan berani melakukan apa saja. Hanya meriam air dan gas air mata yang bisa membubarkannya. Kerumunan ini tidak hanya di jalanan, tapi juga di dunia maya, kebencian akan semakin menjadi apabila ada provokasi, apalagi yang memprovokasi satu “kelompok” dengan kita (in-group), bisa kelompok agama, kelompok suku, kelompok preferensi, bahkan hanya karena warna baju yang sama. Pada masa perang dunia kedua antara tahun 1941-1945, ada seorang guru Jerman yang dihormati oleh siswa-siswanya sebelum perang. Ketika perang pecah dan orang ini menjadi penjaga kamp konsentrasi di Dachau, olah raganya tiap pagi menembaki penghuni kamp sampai mati secara acak untuk menghilangkan bosan. Bagaimana mungkin? Bisa saja, karena semua orang sebangsanya menganggap ras yang dia tembaki (Yahudi, out-group) lebih rendah dari manusia. Dia jadi anonymous di antara bangsanya (Bangsa Arya, in-group), tanggung jawab dan moralitasnya menguap. Menurut teori identitas sosial : In-Group & Out-Group, seseorang bisa dimanipulasi dalam dinamika psikologi massa. Fenomena konformitas individu dalam kelompok macam ini juga pernah diteliti oleh Dr. Philip George Zimbardo, profesor psikologi dari Universitas Stanford pada Agustus 1971. Penelitiannya terkenal dengan nama Standford Prison Experiment. Zimbardo merekrut sukarelawan untuk ikut penelitiannya. Mereka dibayar sama per hari. Ketika dimulai, peserta dibagi secara acak. Satu kelompok menjadi penjaga, satu kelompok menjadi tahanan. Dibuatkan penjara-penjaraan di gedung kampus. Eksperimen direncanakan berjalan 2 minggu. Mereka dibebaskan improvisasi dan diberi seragam yang berbeda antara penjaga dan tahanan. Baru dua hari berjalan, kelompok penjaga sudah memukuli tahanan yang tidak patuh, sementara kelompok tahanan luar biasa takut dengan penjaga dan berusaha “kabur” dari penjara. Padahal mereka bisa saja meminta untuk berhenti.